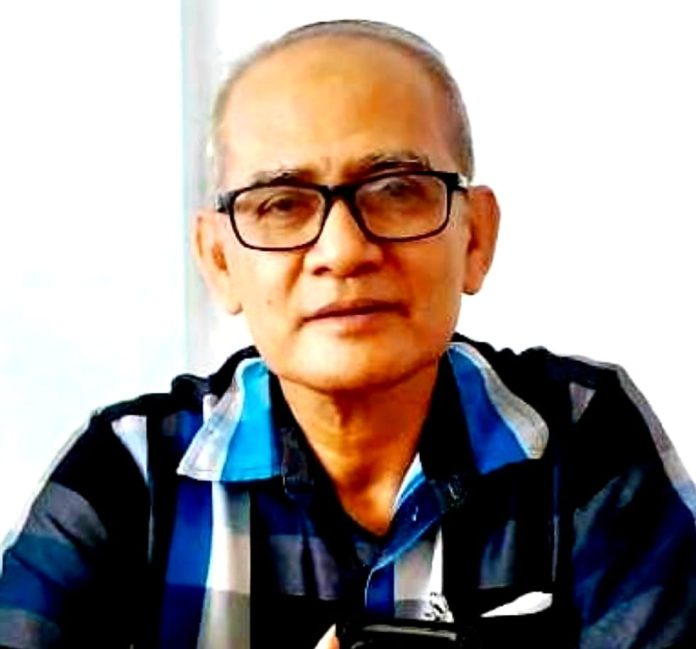Pada masa Sultan Alauidin Riayat Syah (1539 – 1567) zakat duah dikumpulkan walaupun sederhana. Misalnya untuk zakat fitrah yang langsung diserahkan ke Meunasah. Walaupun dulu sudah ada Balai Baitul Maal, tapi fungsinya dulu hanya mengelola keuangan dan perbendaharaan negara.
Dengan semakin berkembang, zakat bisa dikelola individual. K.H Ahmad Dahlan sebagai pimpinan Muhammadiyah mulai mengorganisasi zakat dari anggotanya. Memasuki kemerdekaan pengelolaan zakat mulai terkoordinasi dengan dibentuknya Majlis Islam ‘Ala Indonesia (MIAI) pada 1943.
Pengurusnya terdiri atas Mr. Kasman Singodimedjo, S.M. Kartosuwirjo, Moh. Safei, K. Taufiqurrachman dan Anwar Tjokroaminoto. Mereka berhasil mendirikan 35 Baitul Maal pada 67 kabupaten. Namun Jepang yang khawatir gerakan ini bisa mengganggu, akhirnya membubarkan MIAI pada 24 Oktober 1943. Sejak itulah tak ada lagi lembaga pengelolaan zakat.
Ketika Presiden Soeharto berkuasa, dia menerima masukan dari sejumlah ulama untuk mendorong pengelolaan zakat oleh negara. Hingga dia menyetujui dan mendeklarasikan diri ada amil zakat tingkat nasional. Pak Harto mengirimkan surat ke seluruh gubernur terkait pendirian Bazis di berbagai wilayah mengikuti DKI Jakarta. Namun banyaknya kelompok yang tidak percaya dengan pengelolaan zakat ini akhirnya badan zakat ini mengalami stagnasi dan akhirnya berhenti.
Sampai di awal 1990-an, muncul lembaga zakat swasta yang diinisiasi masyarakat dan dikelola secara modern. Seperti Dompet Dhuafa dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah. Pada era reformasi di masa pemerintahan BJ Habibie, Indonesia pertama kalinya punya Undang-undang pengelolaan zakat yaitu UU nomor 38 tahun 1999.
Ini adalah UU pertama yang terkait dengan zakat dan negara masuk secara formal menjadi amil, pengelola zakat di samping lembaga yang didirikan oleh masyarakat.
Berdasarkan undang-undang ini, pengelolaan zakat terbagi dua menjadi BAZ dan LAZ yang pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sesuai Keppres nomor 8 tahun 2001. Bazis kemudian direvitalisasi menjadi Bazda. Kemudian LAZ tetap jalan sebagaimana mestinya.
Hanya Bazis DKI yang masih dipertahankan karena status DKI Jakarta sebagai ibu kota. Pada era Presiden SBY, UU zakat diganti menjadi UU nomor 23 tahun 2011. Secara formal keterlibatan negara dalam mengelola zakat dimulai pada pemerintahan BJ Habibie, Baznas Pusat di era Gusdur.
Pengamat Ekonomi Syariah IPB, Irfan Syauqi Beik mengungkapkan potensi zakat berdasarkan pusat kajian studi Baznas 2019 sebesar Rp 233 triliun. Tapi dalam studi terbaru naik menjadi Rp 327 triliun.
“Potensinya sangat besar, karena ada potensi zakat perusahaan yang listed di bursa efek hampir Rp 100 triliun,” kata dia kepada detikcom, 25 April 2021.
Irfan mengungkapkan zakat terbagi dua, zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah merupakan zakat yang dibayar menjelang Idul Fitri dengan jumlah 3,5 kg beras atau uang yang nilainya sama dengan beras tersebut.
Lalu zakat maal atau zakat harta termasuk penghasilan, pendapatan dan jasa. Lalu zakat profesi, logam mulia, emas perak, surat berharga, perusahaan perdagangan, sampai pertambangan. “Pada semua harta yang diperoleh dan tidak bertentangan syariah dan hukum negara maka wajib zakat,” ujar dia.
Untuk zakat penghasilan bisa ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab setiap bulan setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas (mengikuti harga buyback emas saat zakat dibayarkan), dengan kadar 2,5%.
Salah satu solusi meningkatkan realisasi pembayaran ZIS ini adalah dengan memberikan pemahaman dan kesadaran kepada para wajib zakat atau ZIS agar melaksanakan kewajibannya. Aparat pemerintah juga harus semakin tekun dan sering mengunjungi warga yang selama ini selalu lalai membayar zakat itu secara persuasif religius. Begitu pun para khatib dan pendakwah ikut menyemarakkan semangat warga membayar zakat untuk membangunkan ”raksasa” yang masih tidur ini. (*)